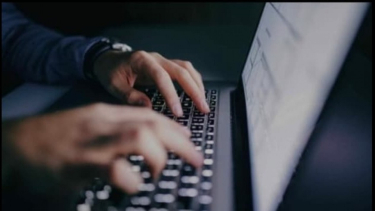Memahami Media Sebagai Bagian dari Ekonomi dan Politik Kekuasaan Versi Mosco
- Unsplash
VIVA – Memahami tentang media, tentu saja tidak hanya soal isi, konteks di dalam pemberitaan maupun informasi yang disampaikan hingga dikonsumsi oleh publik. Pakar komunikasi, Vincent Mosco, dalam bukunya The Political Economy of Communication, menyebut di balik itu ada unsur ekonomi dan politik. Maka dia pun dikenal sebagai tokoh yang mengkaji dari pendekatan ekonomi politik media.
Maka dari Mosco itulah, kita diajak untuk melihat media yang tidak saja dalam fungsi pokoknya sebagai alat informasi, hiburan dan edukasi. Tetapi juga ada pertarungan dari kepentingan ekonomi, pertarungan kepentingan politik.
Ekonomi Politik Media
Secara umum, Mosco mengatakan analisis kritis terhadap media harus bersifat holistik. Tidak sekedar melihat dari sisi internal. Tidak saja melihat pada faktor perkembangan media teknologi. Melainkan ada juga faktor yakni ekonomi dan politik kekuasaan.
Untuk itu, penekanan yang dilakukan oleh Mosco adalah siapa yang memiliki media tersebut, pihak-pihak yang mengatur, serta seperti apa kebijakan yang dibuat, maka itu akan mempengaruhi apa yang terlihat dan terdengar dari media yang dikonsumsi publik setiap harinya.
Media, ekonomi dan politik kekuasaan akan membangun relasi, saling terkait dan terpengaruh. Bagi pemilik modal pada media tersebut, unsur ekonomi akan berada pada faktor yang dominan yang tetap harus dipertahankan. Sementara relasi dengan politik kekuasaan, akan berjalan dan iklimnya akan dipengaruhi bagaimana penguasa, negara, memainkan perannya.
Lalu, di mana letak relasi dengan masyarakat? Karena relasi yang kuat antara pemilik modal dengan negara, ketimbang khalayak media. Tapi dari sisi lain, relasi media dengan negara bisa juga dalam posisi yang berseberangan. Menjadi alat kontrol yang kritis terhadap praktik kekuasaan bernegara.
Apalagi dalam ruang lingkup negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Maka kebebasan dalam sistem demokrasi adalah hak asasi manusia, dan kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi tersebut. Media pun bisa membangun relasi yang kritis terhadap negara, kekuasaan. Tapi lazimnya, relasi seperti ini akan berdampak pada sisi ekonomi media.
Bagaimana bila negara mengambil perannya tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga ikut memainkan peran sebagai pelaku ekonomi? Dedy N Hidayat (2000) dalam tulisannya pada Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni, menyebut kapitalisme industri media era Orde Baru tidak berlangsung alamiah. Tetapi ditentukan oleh konteks maupun karakteristik spesifik dinamika perkembangan kapitalisme era tersebut.
Dia mengutip konsep bureaucratic polity yang dikemukakan Jackson, untuk melihat situasi saat itu. Disebutkan kalau rezim sebagai sumber kekuasaan dan otoritas birokrasi berada di tangan aparat penguasa itu sendiri. Bukan berasal dari partai yang dominan. Pusat kekuasaan ada pada Presiden, sehingga konflik yang terjadi ada pada elit yang secara fisik dekat dengan Presiden.
Masuknya rezim Orde Baru, juga mengawali perubahan iklim media dari rezim sebelumnya, Orde Lama. Dari pers perjuangan atau pers politik, menjadi pers industri.
Pada era pers politik, mengharuskan semua media untuk berafiliasi dengan organisasi atau partai politik tertentu. Susunan staf redaksi pun diisi oleh mereka yang berasal dari kelompok kepentingan itu. Maka lahirlah media-media yang kuat afiliasinya dengan partai atau organisasi. Atau media yang memang dibangun oleh kelompok tersebut.
Seperti Harian Rakyat yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, atau media yang lahir dari ABRI seperti Harian Angkatan Bersenjata. Golkar pada 1971 membuat koran Suara Karya. Lalu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, pada 1991 mendirikan Republika.
Harian Abadi dimiliki Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Nahdlatul Ulama membangun Duta Masjarakat. Sedangkan Muhammadiyah, tiga tahun setelah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912, melahirkan Suara Muhammadiyah (SM) pada 1915, yang mengusung pembaharuan Islam.
Orde Baru kemudian mencabut aturan tersebut. Pencabutan itu diiringi dengan adanya peningkatan ekonomi pada era tersebut. Kondisi itu mendorong pers untuk semakin mengarah ke pasar dan komersil.
Maka tak heran, relasi media dengan politik kekuasaan saat itu cukup kuat. Relasi dibangun bukan saja karena kecondongan media ke penguasa, tetapi juga dilatari oleh faktor pemilik modal. Maka konten media yang disampaikan ke publik, erat kaitannya dengan faktor pemilik, politik dan ekonomi.
Ketika ada media yang memilih untuk tidak ambil bagian dan membangun jarak dari relasi politik kekuasaan, imbasnya adalah pembredelan seperti yang terjadi pada 1994. Sebab secara regulasi, kekuasaan telah mengaturnya sehingga negara punya peran dominan dalam mengatur kehidupan media.
Afiliasi Politik Media
Seperti yang dipaparkan Mosco, media massa tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja, tetapi holistik. Bagaimanapun negara menerapkan sistem pemerintahannya, apakah demokrasi hingga liberal sekalipun, afiliasi media akan selalu ada. Baik itu dari lingkup politik hingga ekonomi bahkan ideologi.
Kecenderungan media untuk berada pada salah satu kubu dalam pemilu di Indonesia misalnya. Kita sudah menjalani beberapa kali pemilu terutama pemilihan presiden. Politik tanah air tidak saja soal partai politik yang berkoalisi mengusung calonnnya. Tetapi ada posisi media juga yang dilihat tidak netral.
Mosco menegaskan, media tidak pernah benar-benar netral. Bahkan banyak pihak juga menilai, netralitas media adalah keberpihakannya. Berpihak pada sisi yang benar. Artinya, ada keberpihakan di sana.
Hanya saja, saat faktor ekonomi, pemilik dan faktor relasi kekuasaan lebih dominan, maka netralitas media itu juga dipersoalkan. Kepemilikan kelompok media, Mosco menyorotinya, akan berimbas pada keragaman suara dan hilangnya sudut pandang yang lain.
Situasi demikian membuat publik hanya melihat dan mendengar cerita dari satu sisi saja. Sedangkan sudut pandang yang lain, sisi cerita yang lain, bisa saja tidak terakomodasi dan hilang dari ruang informasi yang berhak dimiliki oleh publik.
Ketiadaan regulasi yang tegas, juga dianggap membuat relasi media dengan publik semakin kecil. Regulasi dibuat oleh negara, ada faktor politik di dalamnya.
Tidak ada yang benar-benar netral, seperti yang dipaparkan Mosco, membuat publik juga harus kritis. Bahwa apa yang dikonsumsi dari media, ada unsur ekonomi dan kepentingan politik tertentu. Kritis yang dibangun adalah dalam rangka lebih objektif untuk melihat informasi atau berita media. Mana yang benar-benar objektif, dan yang hanya sebagai alat untuk propaganda.
Penulis: Agus Rahmat, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.